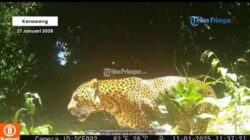Porosmedia.com – Di sudut Kota Bandung yang kian bising oleh klakson kendaraan, seorang pria sepuh dengan gurat wajah yang menyimpan ribuan cerita masih tegak berdiri. Ia bukan sekadar saksi sejarah; ia adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Publik mengenalnya sebagai Abah Landoeng, sosok yang namanya abadi dalam senandung “Oemar Bakrie” karya Iwan Fals.
Lahir nyaris seabad lalu, Abah Landoeng—atau yang memiliki nama asli Landoeng Sastraprawira—adalah sebuah anomali di zaman modern. Di usia yang telah melewati angka 99 tahun, ia masih menyimpan ingatan tajam tentang bagaimana Republik ini merangkak, berdiri, hingga berlari.
Kisah Abah Landoeng adalah narasi tentang pengabdian tanpa batas. Saat perang kemerdekaan berkecamuk, ia bukan hanya mengangkat senjata, melainkan mengangkat kapur. Sebagai guru, ia berkeliling mengajar di bawah bayang-bayang ancaman penjajah. Pendidikan, bagi Abah, adalah senjata paling mematikan untuk membebaskan nalar bangsa.
Salah satu fragmen paling ikonik dalam hidupnya terjadi pada tahun 1955, saat Bandung menjadi pusat perhatian dunia melalui Konferensi Asia Afrika (KAA). Bukan sekadar hadir, Abah memegang peran krusial di balik layar. Ia adalah relawan yang “ditugaskan” untuk mengumpulkan kendaraan bagi para delegasi dunia.
Bahkan, ada cerita unik yang melegenda: ia sempat dititahkan oleh Bung Karno untuk menjadi bagian dari tim yang memastikan cuaca tetap bersahabat selama konferensi berlangsung—sebuah tugas yang ia jalani dengan penuh khidmat demi marwah bangsa di mata internasional.
Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sosok guru sederhana yang mengayuh sepeda dalam lagu “Oemar Bakrie” terinspirasi dari dedikasi Abah Landoeng. Sepeda bukan sekadar alat transportasi baginya; itu adalah simbol kesederhanaan dan keteguhan prinsip.
Ketangguhannya tak main-main. Di usia senja, Abah pernah melakukan aksi yang membuat banyak orang terperangah: mengayuh sepeda hingga ke Tanah Suci selama tujuh bulan untuk menunaikan ibadah haji. Tak hanya itu, ia juga pernah berkeliling Indonesia di atas dua roda, hanya untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi rakyat di pelosok negeri.
Namun, jangan bayangkan Abah Landoeng sebagai sosok tua yang hanya duduk diam mengenang masa lalu. Hingga hari ini, ia adalah aktivis kemanusiaan dan pegiat anti-korupsi yang vokal. Dengan stiker-stiker antikorupsi yang sering ia bagikan, Abah tak segan mengingatkan para pemimpin—dari tingkat daerah hingga nasional—agar jangan pernah mengkhianati amanah rakyat.
”Jangan korup,” pesannya singkat namun tajam, seperti yang pernah ia sampaikan langsung kepada para pejabat daerah di Jawa Barat. Baginya, kemerdekaan yang ia perjuangkan dulu tidak seharusnya digadaikan demi tumpukan harta haram.
Abah juga menjadi penjaga memori kolektif warga Bandung. Ia fasih bercerita tentang sejarah TPU Cikadut hingga rincian peristiwa Bandung Lautan Api. Ia seolah menjadi jembatan antara masa lalu yang heroik dengan masa kini yang penuh tantangan.
Setiap langkahnya, setiap kayuhan sepedanya, dan setiap untaian kalimatnya adalah pelajaran tentang integritas. Di tengah dunia yang kian materialistis, Abah Landoeng mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang telah kita berikan untuk tanah air.
Kini, di usia yang hampir satu abad, Abah Landoeng tetap menjadi “Oemar Bakrie” yang nyata. Ia tidak butuh panggung megah untuk dihormati; kehadirannya di jalanan Bandung dengan kesederhanaannya sudah cukup untuk memberi tahu kita: sejarah tidak boleh dilupakan, dan kejujuran tidak boleh mati.