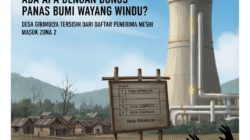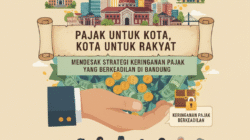Porosmedia.com — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme oleh aparat penegak hukum di Indonesia belakangan kembali mencuat, seiring meningkatnya keresahan publik terhadap aksi kekerasan, pemalakan, hingga pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok preman di berbagai wilayah. Namun, efektivitas dari pembentukan Satgas ini patut dipertanyakan secara kritis, baik dari aspek hukum, sosial, maupun sosiologis.
Mengapa Satgas Premanisme Dibentuk?
Premanisme di Indonesia bukan fenomena baru. Ia tumbuh subur di simpul-simpul ekonomi informal, pasar, terminal, pelabuhan, dan bahkan kawasan industri. Preman kerap menjalankan praktik ‘keamanan informal’ dengan memungut bayaran atas nama ketertiban. Ketika situasi ini makin liar dan menimbulkan keresahan publik, negara hadir melalui pembentukan Satgas sebagai reaksi cepat.
Polda Metro Jaya, misalnya, pernah membentuk Satgas Anti-Preman sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait pemalakan dan kekerasan. Tujuannya: menciptakan efek gentar, merestorasi rasa aman, dan menegaskan kehadiran negara.
Namun, apakah solusi ini menjawab akar persoalan?
Efektivitas dan Realitas Lapangan
Secara jangka pendek, kehadiran Satgas Premanisme mampu meredam aktivitas preman yang kasatmata. Penangkapan massal, patroli intensif, hingga penyisiran titik rawan memberi kesan tindakan tegas.
Namun, berbagai studi kriminologi dan laporan dari LSM seperti Imparsial dan KontraS menunjukkan bahwa tindakan ini cenderung bersifat kosmetik: menekan gejala, bukan menyentuh sebab. Premanisme seringkali merupakan produk dari struktur sosial-ekonomi yang timpang, minimnya lapangan kerja, lemahnya pengawasan aparat, hingga relasi patronase dengan kekuatan politik atau oknum penegak hukum.
Dengan kata lain, premanisme bukan sekadar kejahatan jalanan, tetapi sistem yang mengakar.
Pandangan Hukum: Antara Penegakan dan Pelanggaran
Secara normatif, hukum Indonesia sudah cukup memadai untuk memberantas premanisme. KUHP, KUHAP, dan berbagai regulasi tentang ketertiban umum bisa digunakan untuk menjerat pelaku pemerasan, penganiayaan, atau intimidasi.
Namun, pembentukan Satgas yang bertindak ekstra tanpa mekanisme hukum yang transparan berpotensi menciptakan pelanggaran HAM. Penggerebekan, sweeping tanpa surat tugas, penangkapan tanpa prosedur peradilan, hingga stigmatisasi kelompok tertentu bisa mengarah pada abuse of power.
Dalam konteks itu, Satgas Premanisme bisa menjadi pedang bermata dua: ia bisa menegakkan hukum, tapi juga melanggarnya.
Analisis Sosiologis: Negara dan “Preman yang Diperlukan”
Dalam kajian sosiologis, terutama oleh ilmuwan seperti Clifford Geertz dan Ian Douglas Wilson, preman di Indonesia sering kali tidak hanya dilihat sebagai pelaku kriminal, tetapi juga sebagai “aktor politik informal” yang mengisi kekosongan fungsi negara.
Di beberapa wilayah, preman justru menjadi penyelesai konflik, penjaga keamanan lokal, bahkan alat mobilisasi politik saat pemilu. Ini yang membuat pemberantasan premanisme sering bersifat ambigu—ada preman yang “diperangi”, ada pula yang “dipelihara”.
Satgas Premanisme, dalam konteks ini, hanya efektif jika negara berani bersih dari relasi kuasa semacam itu.
Jalan Tengah: Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Sosial
Pemberantasan premanisme harus disertai pembenahan sistemik. Negara harus hadir bukan hanya sebagai represor, tetapi juga fasilitator ekonomi: membuka akses kerja, memperkuat hukum formal, dan memberdayakan masyarakat sipil.
Satgas Premanisme seharusnya hanya bersifat sementara—sebagai pemadam kebakaran. Untuk solusi jangka panjang, perlu pendekatan terpadu antara Polri, pemerintah daerah, kementerian sosial, dan komunitas lokal.
Penutup: Menghentikan Premanisme atau Mengatur Ulang?
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah negara ingin menghentikan premanisme, atau hanya mengatur ulang siapa yang boleh menjadi preman?
Selama aparat masih terlibat dalam hubungan transaksional dengan preman, selama hukum hanya tajam ke bawah, dan selama ekonomi informal terus dibiarkan tanpa perlindungan legal, maka Satgas—sekeras apa pun—hanya akan menimbulkan efek jera sesaat.
Sebagian masyarakat menilai bahwa pemberantasan premanisme harus berpijak pada hukum, hak asasi, dan perubahan struktural—bukan sekadar operasi bersenjata yang mengundang tepuk tangan sesaat.